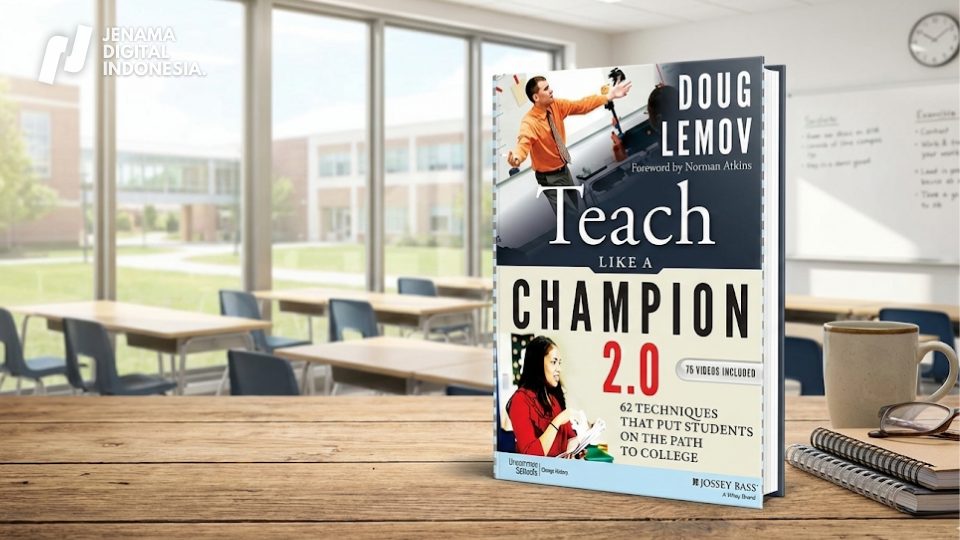Clayton Christensen dalam The Innovator’s Dilemma menjelaskan paradoks yang menarik: organisasi besar gagal bukan karena mereka tidak kompeten, tetapi karena mereka terlalu baik menjalankan sistem lama. Dalam konteks pendidikan, inilah alasan mengapa banyak sekolah sulit berinovasi meski secara teori mereka sadar bahwa perubahan itu perlu.
Pertama, sekolah terjebak dalam pola “melayani kebutuhan saat ini”. Fokus pada ujian, laporan, akreditasi, dan target administratif membuat energi habis untuk menjaga stabilitas. Dalam teori Christensen, inilah jebakan “sustaining innovation” perbaikan kecil yang tidak pernah mengubah inti sistem. Sekolah sibuk membaiki hal lama, bukan membangun hal baru.
Kedua, inovasi disruptif sering dianggap tidak cukup “aman”. Ide seperti pembelajaran fleksibel, personalisasi AI, atau proyek lintas mata pelajaran dianggap terlalu berbeda dari standar yang sudah mapan. The Innovator’s Dilemma menyebut bahwa organisasi besar menolak inovasi bukan karena jelek, tetapi karena terlalu kecil, terlalu baru, atau belum terbukti untuk standar mereka.
Ketiga, struktur sekolah membuat perubahan lambat: rantai birokrasi panjang, aturan ketat, budaya takut salah, dan minim ruang eksperimen. Inovasi butuh ruang gagal, sedangkan sekolah cenderung menuntut kesempurnaan. Dalam bahasa Christensen, sistem lama tidak menyediakan “ruang pasar baru” tempat inovasi bisa tumbuh tanpa tekanan.
Akhirnya, solusi Christensen sederhana namun menantang: buat ruang terpisah untuk bereksperimen. Sekolah perlu unit kecil tim inovasi, kelas pilot, atau program eksperimental yang tidak dibebani standar lama. Dari sinilah inovasi disruptif tumbuh dan perlahan mengubah sistem.
Pada akhirnya, The Innovator’s Dilemma mengingatkan kita bahwa sekolah bukan tidak bisa berinovasi mereka hanya butuh keberanian untuk melepaskan sebagian kontrol. Inovasi lahir bukan dari struktur, tetapi dari ruang bebas yang memberi izin untuk mencoba.